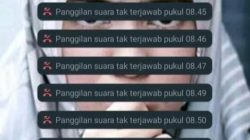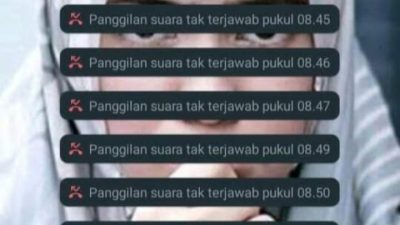Oleh : Dwikki Ogi Dhaswara
Bekaespedia.com_17 Agustus 1819, suara gemuruh bergema di penjuru senja. Dibawah kendali Kapten Ege, pasukan Belanda menuju Bangkakota.
Dibawah rimbun dedaunan yang menyembunyikan mata, mereka menyusuri hutan dengan jejak sepatu besi. Sementara angin menghembuskan bayang-bayang resah.
Kapten Ege maju dengan percaya diri, membawa badai amarahnya yang tak kenal takut. Burung-burung terbang, langit merunduk kelam. Seolah memberi tanda, dibawah rimba yang semakin gelap, langkah mereka semakin samar. Bangkakota sudah menunggu, namun hutan tak membiarkan mereka berkabar.
Kala senja merambat merah, berbaur dalam lengkung malam. Tanpa disadari diujung bayang, mereka sudah diikuti oleh sosok pendekar berbaju hijau kelam, seolah menyatu layaknya dedaunan dan bayangan yang merangkai.
Ia menyusup pelan, bak angin malam yang berbisik pelan di sela dahan, memudar dalam gemetar dedaunan. Langkahnya lembut, nyaris bagai mimpi yang tak tersentuh mata. Akan tetapi, pedangnya bersenandung tajam, menembus gelap tanpa suara.
Dalam sekali sapuan, satu demi satu pasukan Belanda tumbang. Terbawa bisikan maut, terbuai dalam senyap yang lirih. Kapten Ege tak menduga dan semakin takut dengan apa yang terjadi.
Pendekar itu seakan menyulam malam dengan benang nyawa yang rapuh. Ia berkelebat dari pohon ke pohon, dari bayangan ke bayangan tanpa jejak yang mengikat.
Hanya daun-daun jatuh yang mengiringi bisu tumpahnya darah, dan hanya angin yang menyimpan sisa desah terengah-engah yang punah.
Kapten Ege tertunduk, takut dalam gulita tanpa asa. Terdengar suara dalam gemerisik yang merayap, suaranya lekat, seolah dihembuskan dari bayang-bayang pepohonan.
“Sudah puaskah kalian mengelilingi tanah Bangka? Perlu kau ingat, Bangkakota sampai Toboali bukanlah tanah yang mudah untuk kau rengkuh begitu saja, jangan harap kalian bisa membangun markas disini. Pulanglah, aku ampuni kau kali ini!”. Ucap Pendekar.
Begitu lantangnya, namun penuh ketenangan. Suara itu mengiris udara dengan nada tegas yang menghantui.
Kapten Ege terdiam, pulang dengan tubuh gemetar. Dengan ketakutannya ia melaporkan apa yang terjadi, “Pankal Kotta gagal ditaklukan!”.
Belanda menyebutnya dengan Pankal Kotta yaitu Koeboebangka (Kotabangka) atau Bangkakota adalah lokasi yang strategis untuk “kubu” atau “kota” (benteng pertahanan) bagi perlawanan rakyat Bangka.
Tempat untuk menjaga marwah ditengah gugusan pulau, serta tempat rakyat mengukir perlawanan, menyulut harapan yang tak pernah layu.
Untuk itu, hasrat Belanda mengendap. Datang dengan dendam untuk membumihanguskan Bangkakota. Bagi Belanda tempat ini adalah kubu yang perlu dileburkan. Namun, bagi rakyat Bangka, inilah pusat jiwa yang tak boleh tergulingkan.
Memasuki bulan September, Belanda membawa dendam yang menggelegak dalam angin pagi. Mengusung tekad yang tak teringkari. Bangkakota kali ini dikepung di setiap sisi, dari darat dan lautannya.
Dari daratnya dipimpin oleh Kapten Laemlin, membawa 230 pasukan militer, langkah mereka kembali bergema. Dari distrik Pangkalpinang mereka berarak menuju Bangkakota yang teguh berdiri.
Dengan deru senjata, serangan kedua dimulai 14 September 1819.
Disisi lautannya, empat kapal perang mengusung meriam di bawah bendera kebesaran Belanda. Dibawah komando Kapten Baker, mereka maju menghantam garis pantai. Menyeret gelombang ke dalam amarah, beranjak dengan angkuh dan beringas.
Kembali tak disangka-sangka, dengan pergerakan yang sangat cepat oleh rakyat Bangkakota, serangan itu telah terbaca. Bukti bahwa Bangkakota adalah wilayah strategis, itu benar adanya.
Dari setiap sudut wilayahnya, hingga dari tiap reranting yang berbisik dibawah langit mendung pada saat itu, rakyat Bangkakota dan para pendekarnya menjadi tembok yang teguh, satu tubuh, satu nyawa yang tak tergoyahkan.
Dengan taktik yang terlatih, mereka berhasil menggiring pasukan Belanda ke dalam hutan yang rimba akan pepohonan, dimana pohon-pohon kecil dan besar menyatu didalam hutan itu.
Suara senapanpun mulai bergema, diimbangi oleh senyapnya anakan panah. Disisi lain suara dentingan pedang juga telah bergemuruh, menandai adanya pertempuran jarak dekat. Disaat itu juga, seluruh pasukan Belanda diimbangi oleh jumlah rakyat Bangkakota.
Ditengah peperangan, pendekar berbaju hijau kelam kembali muncul, Ia adalah seseorang yang pernah memukul mundur Kapten Ege ke dalam malam yang tak bertepi dan suram.
Geraknya kini lebih cepat, bergerak dalam bayangan rindangnya hutan. Dan ini adalah medan tempur yang diinginkan baginya.
Walaupun disinari oleh bias mentari yang terpancar dari sela dedaunan pohon-pohon. Semua itu tak menyurutkan keahliannya dalam bertarung.
Menguasai Ilmu “Penglimun” dari silat sambut yang bersemi di Tanah Penyampar. Dialah Batin Tikal, bayang di bayang, raba di raba, rasa di rasa. Nama yang ia sebutkan saat menyatakan siapa dirinya, dengan suara tanpa rupa.
Senyap menyelimuti Belanda dengan kecemasan.
Tak ada peluru yang mampu menyentuh Batin Tikal, seakan ia dilindungi oleh takdir yang tak tertulis. Entah tubuhnya yang kebal, atau ia benar-benar diluar jangkauan.
Pasukan Belanda menggigil, melihat bayangnya meliuk diantara cahaya yang pudar. Menghantui mereka, hingga nyali pun layu sebelum keberanian mereka sempat berkobar.
Disetiap sudut, rakyat Bangkakota bergerak seperti ombak yang tak terbendung. Dibawah kepemimpinan Batin Tikal, mereka terlatih dalam daya juang yang menolak tunduk.
Didarat maupun dilautan, mereka melawan dalam satu tarikan napas kebersamaan. Pasukan Belanda terpukul mundur, terbawa oleh arus deras perlawanan yang tak sedikitpun padam.
Kekalahan kembali menghantui pasukan Belanda. Mereka pulang ke Muntok dan Pangkalpinang dengan rasa malu yang tak tertebus dan membisu.
Tercatat, 4 prajurit jatuh dengan nyawa yang melayang, 19 terluka, dan seorang perwira dan puluhan prajurit lainnya terpuruk oleh lapar dan sakit yang menggerogoti raga.
Separuh kekuatan mereka terhenti, tak mampu menantang Bangkakota yang penuh dengan nyala.
Setelah beberapa minggu berlalu, dendam Belanda tak pernah pupus. Di bulan Oktober mereka kembali. Dengan rencana yang terselubung dan licik, mereka datang dan menyerang lagi.
Namun pada saat itu, Batin Tikal sedang berada di Tanah Penyampar bersama keluarganya, sembari mencari persenjataan, menggenggam harapan dalam keterbatasan.
Takdir terjal sudah menanti, bahwa Bangkakota kembali diuji.
Perlawanan memuncak, namun persenjataan kian menipis ditangan rakyat yang berjuang. Bangkakota, yang selama ini menjadi kubu bagi jiwa-jiwa yang merdeka, kini diambang senyap.
Diganti oleh suara rintihan, bersama angin yang kelabu. Tangisan rakyat Bangkakota bergetar, memenuhi langit yang membeku. Rumah-rumah yang dulunya tegak, kini dilahap bara. Dinding yang dibangun dengan harapan kini runtuh, rebah dalam derita.
Dalam deru dan debu dan bara yang menyala merah, sebagian rakyat Bangkakota yang selamat menyingkir ke Utara, menyusuri Sungai Selan dan Sungai Menduk, menuju Kota Beringin yang menunggu, sebagian lagi beranjak ke selatan menuju Nyireh (Sungai Nyireh) mendekati Desa Pergam.
Disisi lain, di Tanah Penyampar, Batin Tikal merasa hancur saat mendengar kabar Bangkakota harus terguling dan kalah. Tak henti-hentinya ia menyalahkan dirinya, tangisan rakyat Bangkakota merasuk ke dasar jiwa yang terluka.
Disetiap derai air mata, amarah Batin Tikal bangkit, meluap, tak tertahan, membakar hatinya hingga menyala. Ia akan menjadi badai, membawa perlawanan hingga dipenghujung perang.
“Perang yang sebenarnya, baru dimulai! Kami bukan bangsa pengecut, kami bangsa pemenang!”. Batin Tikal.
Sedangkan disisi Belanda, ini menjadi kemenangan yang berarti, misi mereka berhasil membumihanguskan Bangkakota. Diakhiri dengan tepuk tangan.
“Overgave”.
Bersambung
Toboali, 13 November 2024